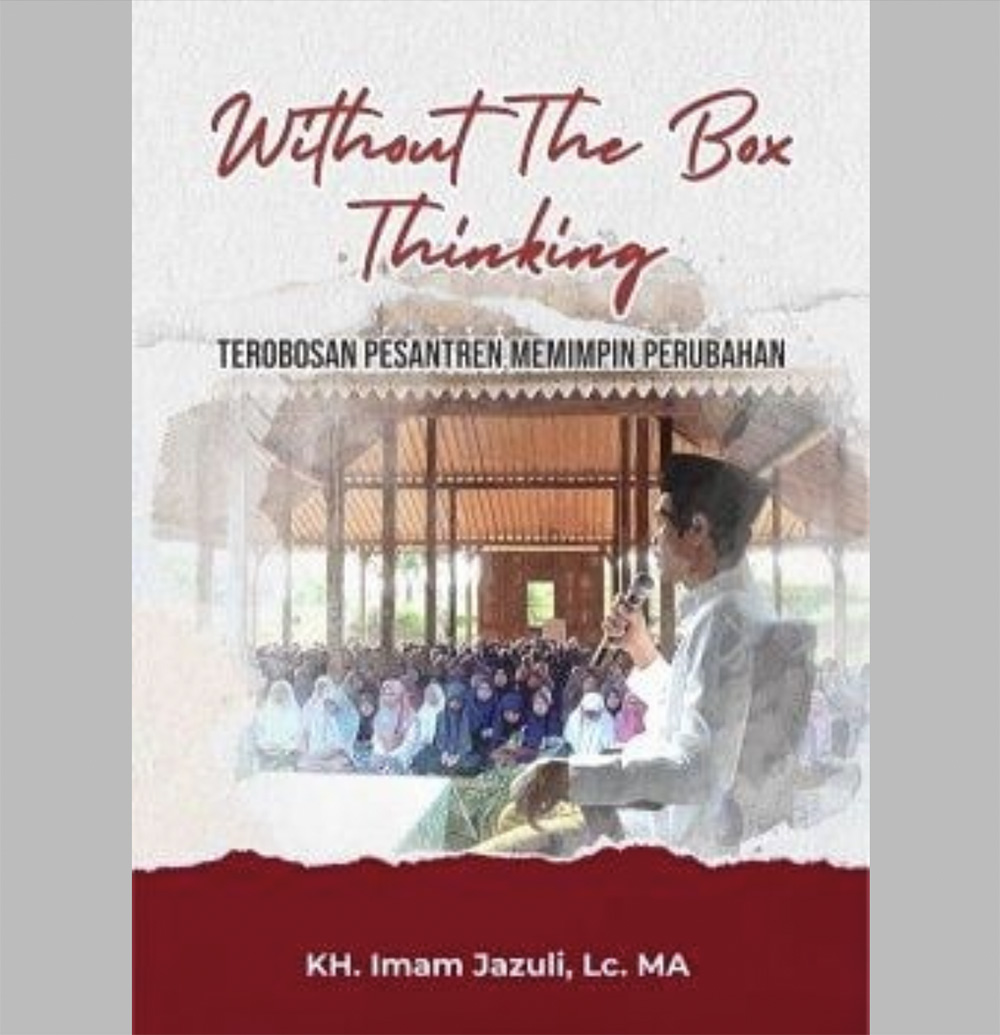
Honoris Causa Pesantren, Kenapa Tidak?
TRIBUNNEWS.COM – “Tepat di jam 10.35 WIB telah terjadi ledakan besar (big bang) di dunia pesantren. Sejak pesantren eksis di Nusantara sekitar 400 tahun lalu, baru kali ini ada terobosan begini.”
Seperti itu pesan tertulis yang dikirim ke saya dari salah seorang profesor yang hadir pada acara inagurasi doktor honoris causa pesantren.
Acara inagurasi sendiri bertempat di Ballroom hotel Aston Cirebon. Tak kurang dari 1.000 orang yang hadir memenuhi ballroom tersebut. Sengaja kami mengundang 58 kiai-kiai senior dari sejumlah pesantren, 17 akademisi dari kampus di Jakarta, Cirebon, dan Bandung, dan 100 profesional yang terdiri dari guru dan profesi lain. Sisanya adalah santri dan wali santri Pesantren Bina Insan Mulia. Kami juga mengundang 10 wartawan cetak, online, dan radio dari Jakarta, Cirebon, dan Bandung.
Penerima gelar honoris causa pesantren pertama adalah saudara Ubaydillah Anwar, seorang santri yang telah lama mengembangkan soft skills dan kecerdasan hati. Lahir dari keluarga pesantren salaf dan memulai nyantri di pesantren salaf di daerahnya, Ubaydillah kemudian meneruskan di Gontor hingga selesai KMI.
Dengan keterampilan menulis dan pidato yang didapat dari pesantren, Ubaydillah masuk ke dunia profesional dan industri lewat tulisan dan pidatonya di bidang pengembangan SDM, khususnya soft skills dan kecerdasan hati.
Tak butuh waktu lama, masyarakat profesional dan industri menerimanya dengan baik. Apalagi ditambah dengan keterampilannya dalam meramu konsep Islam yang didapat dari pesantren dan konsep barat yang didapat secara otodidak dengan modal bahasa Inggris.
Sejak 2004, ia telah menjadi associate trainer, counselor, dan speaker di sejumlah lembaga nasional dan internasional. Antara lain: Nestle Indonesia, ILO (International Labor Organization: Badan Urusan Perburuhan PBB), TrackOne, Gramedia Academy, Indonesia Entrepreneur Society, Data Group, Dibta Group Indonesia, Foster and Bridge Indonesia, dan forum-forum kajian keislaman.
Beberapa BUMN, lembaga pendidikan, dan perusahaan berskala besar, menengah dan kecil, telah mempercayai sebagai narasumber training, workshop, dan seminar. Antara lain: Udiklat PLN, Krakatau Steel, Lexus Indonesia, beberapa CorpU: Corporate University sejumlah BUMN, HERO, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.
Direktur Akademi Soft Skills Indonesia (ASSI) ini telah menulis lebih 45 buku dan lebih dari 1.000 artikel tentang soft skills dan kecerdasan hati yang telah diterbitkan oleh sejumlah media, baik online dan cetak, antara lain: Gramedia, SWA, Mizan, www.e-psikologi.com, www.sahabat.nestle.co.id, majalah Halal MUI, Gontor, dan lain-lain.
Ia juga dipercaya menjadi editor lebih dari 25 buku para tokoh di berbagai level di bidang keislaman, pendidikan, leadership, corporate learning, entrepreneurship, dan lain-lain.
Setelah berkiprah dengan karyanya di masyarakat profesional, industri, dan dunia pendidikan, barulah saudara Ubaydillah diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan profesionalnya di ICS Singapore, ILO (International Labor Organization) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Al-Jamiah Al-Arobiyah di Riyadh.
Dipercaya itu Lebih Tinggi daripada Diakui
Ada yang menarik ketika peristiwa itu menyebar di berbagai media nasional, baik di Tribunnews, Republika online, Kumparan, Kompasiana, FB, IG, dan jaringan WAG. Biasa, pro dan kontra terjadi.
Saya kemudian bertanya ke yang bersangkutan, siapa yang mengundang Anda pertama kali sebagai penerima gelar kehormatan tersebut? Ternyata yang mengundang pertama kali bukan kampus Islam atau pesantren, tetapi Universitas Atmajaya Jakarta, Fakultas Psikologi.
Seiring dengan perjalanan waktu, selama 4 tahun berjalan ternyata luar biasa dampaknya bagi kiprah yang bersangkutan di dunia profesional. Pelan namun pasti, sejumlah BUMN dan kantor kementerian mengundangnya sebagai narasumber yang disejajarkan dengan para doktor kampus. Misalnya di Bank Indonesia sebagai leadership observer, di Kementerian Agama sebagai narasumber pendidikan, dan lain-lain.
PT. Intipesan sebagai lembaga training dan seminar terdepan di Jakarta sering mengundang yang bersangkutan sebagai narasumber topik-topik pengembangan SDM bersama para doktor dari kampus, para dirut BUMN, dan para profesor di bidang manajamen. Demikian juga lembaga Foster and Bridge Indonesia sebagai lembaga training profesional kelas atas di Jakarta.
Saudara Ubayadillah dengan doktor honoris cuasa pesentren yang disandangnya tidak saja diminta mengajar mahasiswa S1 dan S2 di kampus-kampus. Beliau juga dipercaya menjadi panelis yang menguji kemampuan soft skills para kandidat dekan, wakil rektor dan direktur pasca sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang.
Memang kalau membaca ketentuan umum yang ada mengenai aturan penganugerahan gelar kehormatan doktor honoris causa, maka apa yang dilakukan oleh Pesantren Bina Insan Mulia terhadap saudara Ubaydillah Anwar tidak memenuhi persyaratan formal itu.
Namun, saya dan yang bersangkutan memahimanya bukan soal gelar dan prosedur formal. Ini soal sebuah proses perjuangan eksistensi pesantren, kaum santri, dan karya-karyanya di negeri tercinta. Gelarnya sendiri nomor ke sekian. Honoris causa pesantren bukan gelar formal, tapi lebih pada simbol perjuangan dan apresiasi eksistensi santri.
Demikian juga soal pengakuan formal. Tidak masalah juga apabila sekarang ini belum diakui. Kenapa? Pada hubungan antarmanusia dalam bentuk apapun, baik personal, profesional maupun institusional, yang tertinggi tingkatannya bukan diakui melainkan dipercaya.
“Hanya ketika seseorang telah percaya kepada Anda yang akan menjalin kerjasama dengan Anda,” demikian orang bijak berpesan. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri atau bahkan dengan anak sendiri, seseorang tidak akan menyerahkan urusan atau mau untuk bekerjasama apabila kepercayaan (trust) itu belum ada.
Doktor honoris causa pesantren memang tidak diakui kini, tetapi praktik saudara Ubaydillah Anwar membuktikan bahwa yang mempercayainya semakin banyak.
Di masyarakat kita terdapat alumni pesantren yang secara kesalehan dan kompetensi sangat kuat untuk bisa dipercaya di bidang keilmuan tertentu, sayangnya yang selama ini memberi gelar doktor honoris causa maupun professor justru dari lembaga luar negeri.
Idham Chalid adalah santri yang mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar Kairo Tahun 1957. Demikian juga dengan Buya Hamka yang pada tahun 1959 menerima gelar doktor honoris causa juga dari Al-Azhar.
KH. Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan mendapatkan gelar doktor kehormatan (honouris causa) di bidang ekonomi kerakyatan dari American Institute of Management Hawaii, Tahun 2007. Yang lebih mengagetkan adalah honoris causa yang diterima Gus Dur. Menurut catatan NU, Gus Dur menerima gelar kehormatan doktor honoris causa lebih dari enam kali dan itu dari luar negeri semua.
Kenapa Gelar Kehormatan itu Diperlukan?
Banyak yang bilang bahwa saya ini nekat. Saya akui memang begitu. Tapi yang tidak banyak diketahui orang adalah kenapa saya sampai nekat demikian? Ada yang bilang saya hanya cari sensasi saja. Tak bisa saya tolak bahwa akibat dari langkah itu memang sensasi, tapi motivasi saya bukan untuk sensasi.
Beberapa poin memang sudah saya jelaskan di acara tersebut, tapi saya ingin mempertegas lagi di sini kenapa penghargaan kepada alumni pesantren di bidang keilmuan dalam bentuk gelar itu penting dilakukan? Soal namanya honoris causa atau yang lain, itu terserah masing-masing atau terserah mekanisme di internal pesantren.
Ada tiga alasan penting yang perlu saya jelaskan di sini.
Kita lihat berbagai perkumpulan profesional di dunia hari ini sedang giat mengadakan sertifikasi kompetensi di bidangnya masing-masing. Misalnya di ekonomi syariah, IT, akuntansi, dosen mata kuliah tertentu, konstruksi, dan seterusnya.
Sertifikasi kompetensi semakin luas digalakkan, apalagi di zaman digital ini karena ada kecenderungan di masyarakat industri dan profesional bahwa akurasi sertifikasi tersebut lebih tinggi daripada ijazah akademik. Kenapa akurasinya diyakini lebih tinggi? Simpel jawabannya. Yang menentukan nilai seseorang di sertifikasi tersebut bukan semata ujian tertulis seperti di kampus, tetapi karya dan bukti prestasi yang telah dicapai.
Bahkan ke depan, karena akurasinya dinilai lebih tinggi maka wibawanya pun lebih tinggi. Seorang santri bertamu ke saya. Ternyata ia bekerja di sebuah perusahaan IT dunia milik China di Jakarta. Saya tanya kok bisa santri bisa bekerja di sana? Dia jawab, yang ditanya bukan ijazah, tapi kompetensi kerja.
Fakta-fakta di dunia profesional menunjukkan bahwa seseorang yang punya nilai akademik ekselen di bidang tertentu tapi begitu diuji-coba di lapangan, tidak muncul buktinya. Kenapa? Seringkali standar akademik ketinggalan dengan standar profesional yang terus mengikuti perubahan dengan cepat. Di samping itu, namanya di kampus, dasar penilaiannya adalah jawaban tertulis. Itupun banyak yang melakukan plagiarisme, comot sana comot sini, kutip sana kutip sini.
Selain itu, ada gelombang yang tidak bisa dibendung oleh siapa pun hari ini bahwa untuk mendapatkan ijazah akademik semakin mudah dan semakin murah biayanya. Di hampir semua negara telah memberikan layanan pendidikan online yang memungkinkan seseorang mendapatkan ijazah dengan mudah dan biaya yang lebih murah. Ini memang tidak bisa digeneralisasikan ke semua orang. Tapi memang fakta itu ada dan semakin jamak ke depan.
Artinya apa bagi kita? Penganugerahan doktor honoris causa pesantren itu adalah sebuah sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada alumni pesantren di bidang keilmuan tertentu dan itu in sya’a allah kualitasnya akurat, bukan abal-abal atau kaleng-kaleng.
Ke depan, jika alumni pesantren yang telah berkarya itu mendapatkan sertifikasi kompetensi dari perkumpulan pesantren, masyarakat akan lebih percaya dan nilainya jauh lebih tinggi.
Sekarang saya tanya, lebih kredibel dan lebih akurat mana sertifikasi kompetensi di bidang nahwu shorof, misalnya begitu, yang diberikan oleh pesantren dengan yang diberikan oleh fakultas bahasa Arab perguruan tinggi di Indonesia? Semua tahu jawabannya.
Sertifikasi kompetensi juga akan mengikis fenomena ustadz atau da’i dadakan. Banyak yang sekarang terjun di bidang dakwah Islam tapi modalnya motivasi dan belajar dari youtube atau internet. Dasar materinya adalah folk wisdom (hikmah kelas awam) dan common sense (logika umum). Jangankan soal penguasaan fiqih-ushul fiqihnya, urusan makhroj membaca al-Quran saja belum beres. Ini kenyataan bukan?
Yang menjadi masalah hari ini adalah justru lulusan pesantren diberi sertifikasi kompetensi oleh kelompok atau lembaga non-pesantren di bidang keislaman. Ini kiamat sughro buat pesantren. Kenapa? Kemungkinan terjadi like and dislike atau pertimbangan aspek politik menjadi utama. Mau khutbah saja ada batasan ini dan itu. Padahal yang harus kita tegakkan adalah standar keilmuan.
Iklan untuk Anda: Lakukan kebiasaan ini, tekan Diabetes!
Advertisement by
Dua, sebagai apresiasi karya dan eksistensi.
Tradisi memberi apresiasi di dunia Islam itu sudah ada sejak dulu sehingga muncul sebutan al-imam, al-‘alim, al-‘allamah, al-hafidz, asy-syaikh, dan khujjatul Islam untuk al-Ghazali.
Bahkan sebelum pesantren memiliki pendidikan formal seperti sekarang, tradisi penganugerahan gelar pun jamak dilakukan para kiai kepada para tokoh. Oleh para kiai NU, Soekarno diberi gelar sang Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah, sosok pemimpin yang kompeten dan tangguh.
Tidak hanya pesantren, kerajaan dan kesultanan nusantara pun kerap memberikan gelar sebagai apresiasi di bidang tertentu. Pakoe Boewono XII memberikan gelar kehormatan Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) kepada Gus Dur. Beliau dinilai sebagai tokoh agama yang humanis dan punya kepedulian tinggi terhadap budaya daerah.
Apresiasi terhadap karya seseorang di berbagai bidang atau terhadap kebesaran kiprah seorang tokoh menjadi salah satu ciri ketinggian peradaban di bangsa itu. Coba kita lihat sejarah. Kenapa tokoh seperti Abu Nawas itu mendapatkan tempat yang begitu elegan di masa Harun Al-Rasyid? Itu merupakan bukti tingginya peradaban.
Negara-negara yang pernah tinggi peradabannya mempunyai bukti museum, karya para tokoh, bangunan yang bagus, dan seterusnya. Perbincangan manusia di berbagai tempat, dari warung kopi, masjid, gereja, gedung, sekolah, dan lain-lain adalah ide, konsep, dan inovasi. Maka sepertinya agak pas jika ada ungkapan yang mengatakan begini: “Orang kelas atas berbicara ide, orang kelas menengah berbicara peristiwa, dan orang kelas bawah berbicara tentang orang lain.”
Bangsa dengan peradaban rendah, boro-boro menghargai karya. Dikasih buku saja belum tentu dibaca. Diamanati untuk menjaga warisan karya masa lalu saja tidak terurus. Dikasih fasilitas pendidikan gratis pun belum tentu disambut optimal. Mereka berbicara soal kemewahan artis. Tentang bagaimana masuk surga tanpa ilmu, tanpa kerja, dan tanpa karya. Tentang kekayaan orang lain. Tentang bagaimana saling mengalahkan orang lain.
Tiga, sebagai motivasi bagi generasi santri berikutnya.
Motivasi ini bukan untuk yang bersangkutan hari ini. Semua santri sudah mengerti bahwa berkarya itu tujuannya untuk dunia akhirat. Sehingga mereka itu diberi gelar atau tidak, sebetulnya tidak begitu berpengaruh terhadap motivasinya.
Apalagi para santri itu mendapatkan contoh langsung dari para kiainya. Kiai menggunakan tanahnya, rumahnya, sawahnya dan apa yang dimiliki untuk para santri.
Zaman dulu, hampir tidak ada santri yang terkena charge (bayaran) pendidikan. Sekarang ini charge dibutuhkan untuk kepentingan santri langsung dan untuk kelangsungan pendidikan.
Motivasi itu dibutuhkan justru untuk para santri di generasi berikutnya. Jika mereka menyaksikan bahwa para pendahulunya telah mampu sampai pada prestasi tertentu, maka hati mereka akan menggerakkan pikiran dan raganya untuk mencapai yang sama atau yang melebihi.
Misalnya, setelah terbukti bahwa saudara Ubaydillah Anwar mampu eksis dalam pengembangan soft skills dan kecerdasan hati di industri, masyarakat profesional dan di pendidikan Indonesia, saya yakin nanti akan ada generasi santri berikut yang akan meniru langkahnya atau punya langkah lain yang lebih bagus atau yang lebih besar.
Kita tidak tahu bagaimana susahnya dulu menemukan metode membaca kitab kuning seperti yang sudah diajarkan di pesantren-pesantren hari ini. Awalnya itu tidak terbayangkan, bagaimana kalimat dalam bahasa Arab lalu dimaknai sekaligus ditentukan posisi tata bahasanya. Ini temuan keilmuan yang luar biasa. Begitu sudah ditemukan, semua menjadi mudah untuk dipelajari.
Seratus tahun lalu, mungkin hanya Gontor yang mengajarkan bahasa Arab dan Inggris dalam pesantren. Tapi begitu sudah ditemukan metodenya, polanya, dan caranya, sekarang ini dimana-mana sudah ada lembaga yang mengajarkan dua bahasa itu. Bahkan ada yang tiga bahasa atau empat bahasa sekaligus.
Itulah contoh dari bagaimana social learning bekerja. Social learning adalah bagaimana seseorang belajar dari orang lain lalu menerapkan ke dirinya. Social learning ini bekerja di tingkat pribadi, kelompok, umat atau bangsa. Riset-riset di pendidikan dan psikologi menemukan fakta bahwa social learning adalah cara belajar orang dewasa yang sangat efektif, bahkan lebih efektif dari class room learning untuk materi keterampilan.
Pendidikan Pesantren dan Soft Skills
Untuk mendapatkan hasil yang bagus pada semua pekerjaan di dunia ini, maka perlu penerapan hard skills dan soft skills. Ini berlaku pada pak sopir becak, dirut BUMN, dosen, atau guru, dan seterusnya. Mana yang hard skills dan mana yang soft skills?
Hard skill pada sopir angkot adalah kemampuannya dalam menjalankan angkot, paham aturan di jalan raya, paham memperbaiki angkot itu kalau rusak. Sedangkan soft skill-nya adalah kesungguhannya dalam menjalani profesi itu, kreativitasnya kalau sedang sepi, kemampuannya untuk menjaga pelanggan, dan semisalnya.
Hard skill seorang guru adalah memahami langkah-langkah mengajar dari mulai masuk kelas sampai selesai, memahami materi yang diajarkan, mampu membuat soal ujian, dan mampu membuat penilaian. Sedangkan soft skill-nya adalah cintanya pada profesi tersebut, keikhlasannya, kreativitasnya, dedikasinya, amanahnya, dan seterusnya.
Bahkan kalau boleh untuk sekadar menggambarkan, dalam shalat pun ada kegiatan yang bisa disebut sebagai hard skill dan soft skill. Hard skill-nya adalah kemampuan menerapkan prosedur fiqih dari mulai takbirotul ihrom sampai salam.
Sedangkan soft skill-nya adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akhlak setelah shalat dan kemampuannya untuk menghadirkan Allah dalam hati (akidah), baik di dalam maupun di luar shalat.
Hard skills adalah keahlian teknis dan akademis. Sedangkan soft skills adalah kualitas seseorang dalam mengembangkan diri, menjalin hubungan dengan sesama, dan kepemimpinan. Misalnya, menjaga emosi, terus belajar, kerjasama, berkomunikasi, ketajaman tujuan, kreativitas, kesabaran, dan seterusnya.
Empat sifat wajib Rasul yang kita kenal, yaitu Sidik, Amanah, Tabligh, dan Fathonah masuk dalam soft skills utama (core skill) yang berlaku di seluruh dunia. Kunci sukses berkarier di bidang apapun, tidak mungkin meninggalkan salah satu dari empat itu.
Jika kedua keahlian tersebut sangat penting untuk mendapatkan hasil yang bagus, lalu mana yang sangat menentukan peranannya? Baik riset dan praktik membuktikan bahwa 70% kesuksesan pekerjaan dimainkan oleh soft skills seseorang. Walupun seseorang sudah ahli di bidang tertentu, tapi jika hati dan pikirannya error, misalnya dengki, stres, ogah-ogahan atau marah, sudah pasti hasilnya akan kurang bagus.
Mau shalat seribu rakaat pun, namun jika tidak didukung dengan ilmu untuk mengaktifkan hati dan pikiran agar menghasilkan kedekatan dan akhlak, tetap saja oleh al-Quran disebut pendusta agama. Meski demikian, mengerjakan shalat sesuai prosedur fiqih tetaplah wajib.
Pesantren sebenarnya gudangnya soft skills. Contoh yang sederhana adalah public speaking atau komunikasi publik Di luar pesantren, kegiatan itu berbayar tinggi. Apalagi jika yang menjadi mentornya artis atau orang terkenal, seperti Helmi Yahya, Tontowi Yahya, atau Najwa Shihab. Tapi di pesantren, kegiatan public speaking gratis dan boleh berlatih terus menerus. Hampir setiap pesantren hari ini punya program latihan pidato.
Cuma di sini yang perlu menjadi catatan adalah bahwa hampir seluruh kegiatan pengasahan soft skills di pesantren itu masih berjalan alami, alias belum tersentuh oleh konsep sains dan standar kompetensi profesional. Banyak santri yang dulu jago pidato tapi di luar berhenti. Banyak yang bagus leadership-nya namun di luar tidak demikian.
Kenapa? Jawabannya adalah pengetahuan. Dengan pengetahuan maka seseorang punya banyak pilihan. Tanpa pengetahuan, seorang anak petani hanya berani bercita-cita menjadi petani seperti orangtuanya. Tapi dengan pengetahuan, ia punya banyak pilihan.
Di sinilah pesantren butuh pengetahuan baru dari kegiatan soft skills yang sudah dijalani para santri supaya mereka punya banyak pilihan.
Without the BoX Thinking adalah rubrik khusus di tribunnews.com di kanal Tribunner. berisi artikel tentang respon pendidikan Islam, khususnya pesantren terhadap perubahan zaman dan paparan best practices sebagai bahan sharing dan learning di Pesantren Bina Insan Mulia. Seluruh artikel ditulis oleh KH. Imam Jazuli, Lc, MA dan akan segera diterbitkan dalam bentuk buku. Selamat membaca.
*Penulis adalah Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia 1 dan Bina Insan Mulia 2 Cirebon. Pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015. Penulis merupakan alumnus Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; juga alumnus Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; dan alumnus Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies.*
link : https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/02/23/honoris-causa-pesantren-kenapa-tidak

0 comments
Write a comment